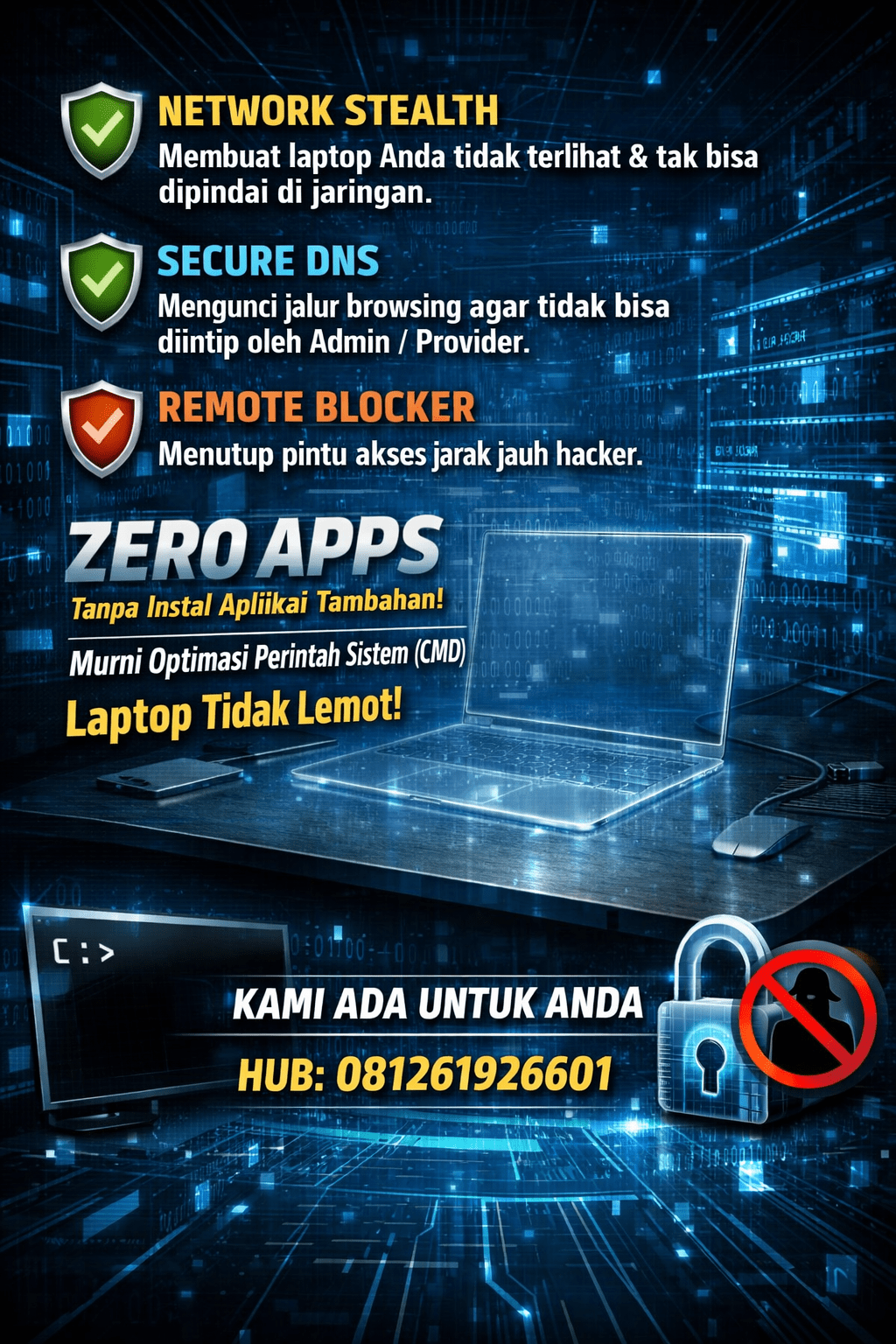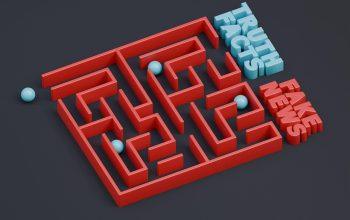Oleh: Abdul Hamid
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas
Jumat,19 Desember 2025 | 19.15 WIB
KABAMINANG.com – Bencana alam merupakan peristiwa yang sering melanda berbagai wilayah di Indonesia, mengingat kondisi geografis dan iklim yang rentan terhadap gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Salah satu bencana yang berulang dan berdampak luas adalah banjir, termasuk yang terjadi baru baru ini di Sumatera, salah satunya terjadi di Provinsi Aceh.
Banjir bandang di Aceh sangat menimbulkan kerugian material serta penderitaan bagi masyarakat Aceh. Banyak masyarakat disana yang kelaparan, kehilangan rumah, serta lambatnya distribusi bantuan semakin memperparah kondisi disana.
Namun, di balik tragedi kemanusiaan tersebut, muncul fenomena sosial yang patut menjadi perhatian serius, yakni terdapat perbedaan respon sebagian masyarakat Indonesia terhadap korban banjir Aceh karena sering dikaitkan dengan sejarah politik di masa lalu. Banyak masyarakat yang menanggapi peristiwa dengan sinis dan minim empati Fenomena ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya menguji kesiapan negara, tetapi juga menguji kualitas nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa.
Artikel ini tidak hanya mengkaji banjir di Aceh sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai ujian implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks kemanusiaan dan persatuan nasional di tengah perbedaan sejarah dan dinamika politik daerah
Kondisi Banjir di Aceh dan Dampaknya bagi Masyarakat
Kondisi banjir di Aceh pada Desember 2025 ini telah mencapai level darurat nasional dengan dampak yang sangat luas dan melumpuhkan. Bencana ini juga disebut sebagai “Tsunami Kedua” yang menyebabkan setidaknya 456 orang meninggal dunia dan memaksa lebih dari 800.000 warga mengungsi ke posko darurat yang kini mulai krisis sanitasi. Banyak wilayah, seperti di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, sempat terisolasi total akibat jembatan putus dan jalan nasional yang tertutup material longsor, bahkan warga di titik-titik tertentu sampai harus mengibarkan bendera putih karena kehabisan bahan makanan. Secara ekonomi, dampak banjir ini sangat menghancurkan karena merusak lebih dari 138.000 hektar sawah yang mengancam ketahanan pangan, serta ribuan rumah warga rusak parah bahkan ada yang hilang tersapu arus. Selain kerugian material yang mencapai triliunan rupiah, masyarakat kini harus menghadapi ancaman penyakit setelah banjir dan lumpuhnya aktivitas pendidikan akibat ratusan gedung sekolah yang tertimbun lumpur, yang secara keseluruhan menguji daya tahan sosial dan kecepatan respons kemanusiaan di Aceh.
Fenomena Rendahnya Empati di Ruang Publik
Ditengah kondisi sulit itu, muncul fenomena sosial yang menunjukkan rendahnya empati sebagian masyarakat. Hal ini tampak dalam komentar komentar sarkas di ruang publik, khususnya dalam media sosial. Alih-alih mengekspresikan solidaritas, sejumlah komentar justru menampilkan nada sarkas dan mengaitkan bencana dengan stigma sejarah politik Aceh.
Beberapa komentar yang beredar, misalnya, menyatakan “lapar minta makan, kenyang minta merdeka” (@h* ty), atau “gak bisa ke sana belum ada pasport” (@Rah*d). Komentar lain bahkan mempertanyakan secara sinis, “presiden Aceh ke mana?” (@rub*jnee). Komentar-komentar tersebut tidak diarahkan untuk memahami kondisi korban atau mendorong solusi, melainkan stigma yang masih belum hilang walaupun ditengah kondisi bencana.
Kehadiran komentar semacam ini menunjukkan bahwa ruang publik digital belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang empati, melainkan masih sering dimanfaatkan untuk membuat narasi diskriminatif kepada kelompok tertentu.
Sejarah Politik dan Nilai Kemanusiaan
Aceh memang memiliki sejarah politik yang kompleks, termasuk konflik bersenjata dan tuntutan politik di masa lalu adalah fakta yang tidak bisa dihapus. Namun, menjadikan sejarah tersebut sebagai dasar untuk mengurangi empati terhadap masyarakat Aceh saat ini merupakan sikap yang salah. Sikap tersebut mencerminkan menurunnya nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa.
Bencana alam bersifat netral dan tidak mengenal identitas politik. Korban banjir adalah warga yang memiliki hak atas perlindungan dan solidaritas, tanpa memandang latar belakang sejarah daerahnya. Ketika stigma sejarah dijadikan pembenaran untuk menghilangkan rasa kemanusiaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya etika sosial, tetapi juga integritas moral bangsa.
Read More:
- 1 Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Tekankan Tidak Ada “Kamar dalam Kamar”, Disiplin dan Kinerja Harus Ditingkatkan
- 2 Drama Sesko di Menit Akhir Bawa Manchester United Raih Tiga Point
- 3 SD Tahfidz Rahmatul Aisy Alahan Panjang Galang Donasi Rumah Siswa Terdampak Angin Kencang Puting Beliung dan Antarkan Bantuan.
Pancasila sebagai Landasan Etika Sosial
Dalam perspektif Pancasila, sikap tidak berempati terhadap korban bencana bertentangan secara langsung dengan sila ke 2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menegaskan bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan tuhan. Penghinaan atau pengabaian terhadap penderitaan korban bencana merupakan bentuk ketidakadilan dan ketidakberadaban.
Selain itu, sila ke 3, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman sejarah dan budaya. Persatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah, tetapi juga sebagai kesatuan rasa dan solidaritas. Ketika sentimen kedaerahan dan stigma sejarah dibiarkan berkembang, maka nilai persatuan kehilangan maknanya
Bencana alam seharusnya dipahami sebagai tragedi kemanusiaan yang menuntut solidaritas, bukan sebagai ruang untuk penghakiman politik atau historis. Mengaitkan penderitaan korban dengan masa lalu konflik hanya akan memperlebar jarak sosial antarbangsa bahkan juga menghilangkan rasa empati dikala terdampak bencana.
Dalam konteks ini, empati merupakan syarat utama bagi terwujudnya kehidupan berbangsa yang beradab. Tanpa empati, nilai-nilai Pancasila berisiko hanya ada secara teks tetapi mati secara nilai. Ia tidak lagi jadi pedoman hidup bangsa,melainkan hanya sebagai slogan politik.
Peran Negara, Masyarakat, dan Generasi Muda
Penanganan bencana merupakan tanggung jawab utama negara, mulai dari mitigasi hingga pemulihan pascabencana. Namun, implementasi nilai Pancasila tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, melainkan juga pada peran masyarakat, terutama dalam menjaga solidaritas dan menghindari narasi yang dapat memecah belah bangsa.
Media sosial hari ini menjadi ruang penting pembentukan opini publik. Ia bisa menjadi jembatan empati, tetapi juga bisa berubah menjadi panggung penghakiman. Pilihan ada pada kita. Apakah kita ingin ruang publik dipenuhi suara yang menguatkan, atau komentar yang menambah beban psikologis korban?
Generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah ini. Dengan akses informasi dan kemampuan membentuk narasi, anak muda dapat memilih untuk tidak ikut arus sarkasme. Mengkritik kebijakan boleh, mengingatkan sejarah sah, tetapi memanusiakan korban bencana seharusnya tidak pernah ditawar..
Kesimpulan
Pada akhirnya, bencana adalah momen refleksi. Menguji seberapa dalam kita memahami makna kebangsaan. Apakah Indonesia hanya kita bayangkan sebagai peta dan sejarah, atau sebagai persekutuan manusia yang saling peduli?
Aceh hari ini sedang basah oleh banjir. Besok, bisa jadi daerah lain yang mengalami hal serupa. Saat itu tiba, kita tentu berharap diperlakukan sebagai sesama, bukan sebagai simbol masa lalu. Karena dalam tragedi kemanusiaan, yang dibutuhkan bukan penghakiman, melainkan kehadiran.
Jika empati kita berhenti pada batas sejarah, maka persatuan hanya akan menjadi jargon. Namun jika kita mampu melihat penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita bersama, di situlah Indonesia menemukan maknanya yang paling hakiki. Terlepas dari perbedaan sejarah dan dinamika politik daerah, solidaritas nasional merupakan esensi kehidupan berbangsa. Hanya dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai hidup yang terwujud dalam sikap dan tindakan, bangsa Indonesia dapat tetap berdiri sebagai bangsa yang beradab dan bersatu.